Menikah Tanpa Cinta, Why Not?
Friday, January 13, 2006 - Menikah Tanpa Cinta, Why Not?
Tak bisa dibayangkan pada zaman sekarang menikah tanpa pacaran terlebih dahulu. Dengan bersusah payah meniti dari waktu ke waktu—di samping pula banyaknya biaya yang dikeluarkan—untuk dapat mengetahui lebih dalam kepribadian masing-masing. Hingga saatnya pun tiada kata-kata yang terucap dari bibir mereka kecuali: I Love You.
Dengan semaian kalimat itu cinta semakin tumbuh, tumbuh, dan tumbuh sampai mereka terikat benar dalam suatu tali yang bernama pernikahan. Namun sebagiannya malah terjerumus dalam buaian dunia hingga batasan, aturan, dan kesucian pun ternoda. Bila perlu—entah karena tidak tahu atau disengaja—ada ruh yang terbentuk sebagai penghuni baru sang rahim layaknya inden sebuah mobil.
Malah yang lebih ekstrim, mereka memproklamirkan diri untuk tidak menikah, karena buat apa menikah kalau mereka sudah sama-sama cinta dan sudah sama-sama tahu tentang diri masing-masing, itu alasan utamanya.
Lalu tak bisa dibayangkan pula pada zaman sekarang menikah dengan gaya Siti Nurbaya yang tidak perlu ketemu dengan pasangannya, dijodohkan, ditanya mau atau tidak, lalu jadilah mereka mengucapkan perkataan yang berat hingga mengguncang ‘arsy.
Tak bisa dibayangkan lagi pada zaman sekarang yang semua ukurannya adalah kebendaan dan kedudukan, menikah tanpa cinta, tanpa rasa kasih sayang yang muncul tiba-tiba saat mendengar lagu-lagu melankolis, saat hujan rintik-rintik hingga menderas, saat berjalan di rel panjang lurus hingga ke ujung cakrawala, saat ombak menjilat jejak-jejak tapak kaki di tepian pantai pasir putih.
Lalu tak bisa dibayangkan lagi pada zaman sekarang yang hampir semua penghuninya memuja kemewahan, sebagian penghuninya yang lain menikah dengan bermodalkan azzam dan pencarian remah-remah rahmah Sang Kuasa.
Betulkah? Faktanya adalah sebaliknya. Saat ini semuanya tidak hanya bisa sekadar dibayangkan tapi bahkan bisa disaksikan, betapa banyak jiwa-jiwa memilih pasangannya dengan perjodohan bergaya Siti Nurbaya, tanpa pacaran, tanpa cinta, dan hanya bermodalkan kedekatannya pada Sang Pemilik Jiwa, tidak dengan bertumpuk-tumpuk hepeng dan emas permata.
Lalu setelahnya, bisakah tumbuh tunas-tunas cinta, menjadi pepohonan kasih sayang, berbuah kata-kata manis yang memerah, dengan dedaunan lebat penyejuk hati? Bisakah?
Lalu bisakah cinta itu tumbuh di saat belahan jiwanya tidak mempunyai kecantikan dan kegagahan dengan parameter barat? Tidak sekaya para emir pemilik ladang minyak? Ataupun tidak mempunyai catatan darah biru bangsawan Jawa, trah habaib, ataupun klan ternama? Bisakah?
Bisa. Karena para jiwa itu menyadari parameter mereka bukan duniawi. Parameter mereka adalah ukhrawi, yang tak bisa dinilai dengan segala isi bumi dan langit. Parameter mereka adalah keridhoanNya. Parameter mereka adalah addiin yang suci dan putih. Parameter mereka adalah kelangsungan penerus di jalan terjal, berliku, sepi, penuh onak dan duri, thoriqudda’wah.
Bisa, Karena para jiwa itu menyadari bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya pemilik segala cinta di alam semesta ini, yang membolak-balikkan hati, pemilik segala jiwa, pemilik segala rindu, mahakaya, mahamurni. Lalu mengapa ia tidak mengetuk-ngetuk pintu langit, meminta kepadaNya saat ia membutuhkan cinta itu tanpa menodai kesucian agama ini, kesucian diri, dan kesucian calon belahan jiwanya.
Bisa, jawab Anis Matta. Sudikah mendengar sedikit ceritanya pada kitab ”Biar Kuncupnya Mekar Jadi Bunga”? (Pustaka Ummi, 2000) Inilah kisah indah itu.
Abdurrahman Ibn Al-Jauzy menceritakan dalam Shaed Al-Khathir kisah berikut ini: Abu Utsman Al-Naisaburi ditanya: ”amal apakah yang pernah anda lakukan dan paling anda harapkan pahalanya?”
Beliau menjawab, ”sejak usia muda keluargaku selalu berupaya mengawinkan aku. Tapi aku selalu menolak. Lalu suatu ketika, datanglah seorang wanita padaku dan berkata, ”Wahai Abu Utsman, sungguh aku mencintaimu. Aku memohon—atas nama Allah—agar sudilah kiranya engkau mengawiniku.” Maka akupun menemui orangtuanya, yang ternyata miskin dan melamarnya. Betapa gembiranya ia ketika aku mengawini puterinya.
Tapi, ketika wanita itu datang menemuiku—setelah akad, barulah aku tahu kalau ternyata matanya juling, wajahnya sangat jelek dan buruk. Tapi ketulusan cintanya padaku telah mencegahku keluar dari kamar. Aku pun terus duduk dan menyambutnya tanpa sedikit pun mengekspresikan rasa benci dan marah. Semua demi menjaga perasaannya. Walaupun aku bagai berada di atas panggang api kemarahan dan kebencian.
Begitulah kulalui 15 tahun dari hidupku bersamanya hingga akhir ia wafat. Maka tiada amal yang paling kuharapkan pahalanya di akhirat, selain dari masa-masa 15 tahun dari kesabaran dan kesetiaanku menjaga perasaannya, dan ketulusan cintanya.
Dan kesetiaan itu adalah bintang di langit kebesaran jiwa. (p26-27).
Wahai saudaraku, jika tiba-tiba kesadaran itu muncul setelah membaca dan merenung, lalu mengapa takut untuk menikah? Mengapa takut tiada hari esok yang cerah tanpa “bondo”? Mengapa takut tiada martabat tertinggi sedangkan martabat itu bisa engkau rengkuh saat menjadi orang yang paling bertaqwa, bukan sekadar martabat dunia yang remeh temeh itu? Mengapa takut tidak ada cinta di antara kalian, wahai saudaraku?
Aku katakan saja untuk terakhir kalinya: ”Menikah tanpa cinta, why not?”
Ps. Untuk kawan-kawan di timur dan utara.
riza almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
kali banjir, Citayam 05:52 12 Januari 2006









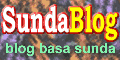


No comments:
Post a Comment