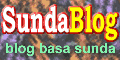BIOLA TAK BERDAWAI
Biola Tak Berdawai
:Sebuah Roman
Seno Gumira Ajidarma & Sekar Ayu Asmara
Penerbit PT Andal Krida Nusantara (Akur)
Cet. II Maret 2004
Tanpa dawai, bagaimanakah biola bisa bersuara? Biola bagaikan tubuh, dan suara itulah jiwanya—tetapi di sebelah manakah dawai dalam tubuh manusia yang membuatnya bicara? Jiwa hanya bisa disuarakan lewat tubuh manusia, tetapi ketika tubuh manusia itu tidak mampu menjadi perantara yang mampu menjelmakan jiwa, tubuh itu bagaikan biola tak berdawai. (Prolog, hal 1)
Buku ini ditulis berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara. Dengan cara pandang seorang anak tunadaksa (dengan banyak cacat yang diderita) bernama Dewa. Autistik, bisu, tubuh kecil yang tidak bisa berkembang, mata terbuka tapi tidak melihat, telinga yang bisa menangkap bunyi tapi tidak mendengar, jaringan otak yang rusak, leher yang selalu miring, kepala yang selalu tertunduk, wajah bagaikan anak genderuwo adalah gambaran dari anak itu.
Sebagai salah satu bayi yang tumbuh besar sampai umur delapan tahun—yang di luar perkiraan kebanyakan orang di panti asuhan tersebut, ia adalah belahan jiwa dari salah seorang pengasuhnya, Renjani. Renjani bersama Mbak Wid adalah pengurus panti asuhan yang bernama Rumah Asuh Ibu Sejati, terletak di daerah para pengrajin perak bernama Kotagede di pinggiran kota Yogyakarta. Tempat di mana mereka menampung bayi-bayi yang tidak dikehendaki, karena cacat ataupun karena hasil dari hubungan gelap.
Renjani bersama Dewa mengarungi pergiliran waktu dengan menyaksikan kedatangan para bayi tunadaksa yang cepat pula meninggalkan mereka karena kematian, meninggalkan mereka menuju ke pekuburan bayi. Begitu pula dengan Mbak Wid, seorang dokter kepala, yang di siang harinya mengenakan pakaian putih-putih, tapi di saat malam tiba, ia berubah menjadi perempuan berbaju hitam-hitam yang begitu percaya ramalan kartu Tarot dan menyepi di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan seratus lilin. Selalu, Renjani menemani Mbak Wid dalam permainan kartu itu, tentu dengan Dewa yang tetap terdiam membisu, dengan leher yang selalu miring, dan kepala yang selalu tertunduk.
Sampai suatu ketika saat Dewa mendengar alunan biola dari sebuah CD, sebuah kekuatan mampu membuat kepalanya terangkat—hanya sepersekian detik, dan Renjani—ibunya yang mantan penari balet—melihat itu! Renjani menghambur memeluknya. “ Dewa, Dewa—Dewa suka ibu menari ya? Ah, Ibu sayang sekali sama kamu Dewa!”
Sepersekian detik itulah yang kemudian membawa Renjani dan Dewa melihat Ballet Ramayana yang dimainkan setiap bulan purnama di Candi Prambanan. Lalu berkenalan dengan pemuda yang lebih muda usia daripadanya. Bhisma, salah seorang pemain biola dari pertunjukan itu selalu memperhatikan Renjani saat pertunjukan berlangsung. Singkat cerita, Bhisma semakin akrab dengan Renjani, pun dengan Dewa yang ia sebut sebut sebagai biola tak berdawai.
Tapi keakraban dan benih cinta yang mulai tumbuh itu rusak saat Bhisma memaksa Renjani menerima dirinya karena itu berarti mengusik masa lalu Renjani yang gelap, yang menjadi satu-satunya alasan mengapa ia pindah dari Jakarta ke tempat sepi ini. Ia belum sanggup berdamai dengan masa lalunya. Masa lalu yang merusak kehormatannya sebagai seorang perempuan. Ia diperkosa oleh guru baletnya.
Jejak-jejak gelap itu menjelma menjadi segumpal daging yang Renjani secara ceroboh menggugurkannya. Lalu menjadi kanker yang membuatnya koma selama seminggu dan akhirnya berkumpul bersama bayi-bayi tunadaksa yang tidak sanggup bertahan hidup di dunia. Bhisma menyesal atas pemaksaannya itu.
Penyesalan yang hanya bisa membuatnya melakukan sebuah konser tunggal. Di kuburan Renjani. Di kuburan para tunadaksa itu. Memainkan resital gubahannya yang baru terselesaikan dan tak sempat tertunaikan untuk dimainkan di hadapan Renjani.
Tapi walaupun terlambat konser itu bagi Dewa adalah konser dari seribu biola, seribu harpa, seribu seruling, seribu piano, seribu timpani, seribu cello, seribu bas betot, seribu harmonica, seribu gitar listrik, dan seribu anggota paduan suara malaikat dari sorga. Membuat langit ini penuh dengan cahaya dan lapisan-lapisan emas berkilauan. Dan yang mampu membuat Bhisma tertegun, mampu membuat biola itu berhenti sejenak, mampu membuat Dewa berkata: “D..de….f….faa…shaa…shaa…aang…iii…buuu.”
Dewa sayang kamu Renjani.
Secara keseluruhan roman ini bercerita dengan sederhana sekali. Sekali lagi, sederhana sekali. Ada yang membuatnya beda dan menjadikan novel ini berciri khas unik yaitu penyelipan kisah-kisah pewayangan, kakawin Bharata-Yuddha beserta para tokoh-tokohnya, Drupadi, Pandawa, Kurawa, Bhisma, Sengkuni, Dorna, dan yang lainnya. Kisah-kisah yang terlupakan oleh saya. Namun sempat membangkitkan memori bahwa saya sempat membaca komiknya waktu masih SD dulu.
Filmnya meraih berbagai penghargaan internasional namun roman adaptasi dengan judul sama ini bagi saya biasa-biasa saja. Belum menggugah rasa kebahasaan saya walaupun ditulis oleh seorang yang bernama Seno Gumira Ajidarma. Penulis serba bisa Indonesia yang paling produktif—sebagaimana ditulis dalam kata pengantar buku itu—yang piawai sekali memainkan kata-kata dan sekali lagi menurut penulis kata pengantar tersebut mampu menangkap echo cinta dari film itu. Bagi saya Seno tidak sepiawai saat memainkan kata dan cinta tentunya dalam “Sepotong senja untuk Pacarku.” Karena ia terkungkung dalam sebuah skenario? Entah. Buku ini cukup dibaca saat waktu senggang saja.
Namun kavernya bagi saya mampu untuk “menutupi” kekurangan ini. Indah. Biola tak berdawai, kupu-kupu jingga, warna hitam yang dominan adalah sebuah citra tepat dari sebuah sampul yang menggambarkan isi buku ini. Sebuah asa akan asmara, yang hilang terampas oleh duka dan waktu.
Riza Almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
06.08 23 Juni 2007