19 September 2000
19 September 2000
Kebiasaan setiap pagi yang saya lakukan sesaat sebelum berangkat ke kantor adalah melihat dua prajurit saya yang masih terlelap tidur itu. Lalu saya tatap wajah-wajah polos mereka. Mengelus-elus kepala dan mencium pipi-pipi mereka. Sungguh pada saat itulah kebahagiaan itu terasa hinggap. Seiring beratnya rasa untuk meninggalkan mereka. Ada sepucuk doa terselip untuk mereka, semoga Allah mengekalkan kebersamaan ini sampai di jannah-Nya.
Bagaimana tidak bahagia, jikalau saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa itu di tengah waktu yang seakan mendera saya dengan rutinitas setiap harinya. Pergi saat matahari belumlah muncul, dan pulang saat matahari sudah tenggelam di peraduannya. Maka pertemuan dan kebersamaan itu terasa singkat di setiap malamnya saat bergumul dengan keceriaan mereka. Saat si sulung mengulang kembali pelajarannya dan saat si bungsu ini mencoba dengan terbata-bata mengulang hafalan bunyi hurufnya. Lalu malam kian menjelang dan tidurlah mereka kembali dibalut mimpi di kamar yang terpisah.
Sebelumnya kembali rutinitas mengasyikkan dilakukan dengan merangkul mereka satu-persatu.
”Ayo Haqi, peluk Abi dulu,” pinta saya. Haqi pun bergegas menghampiri saya, dan saya memeluknya dengan erat, erat sekali. Tidak sekadar pelukan biasa. Saya usahakan tangan si Haqi pun memeluk punggung saya. Agar terasa kehangatannya. Agar terasa kasih sayangnya.
“Ayo cium Abi…”pinta saya lagi. Lalu ciuman itu mendarat di bibir dan kedua pipi saya. Terakhir ciuman saya mendarat di keningnya. Begitu pula saya lakukan kepada si bungsu.
Indah sekali rasanya. Ada keinginan abadi untuk selalu melakukan ini, tapi sungguh saya tak bisa mengekang waktu agar berhenti berputar untuk kedua anakku agar senantiasa mereka tetap menjadi anak-anak yang lucu supaya saya dapat dengan leluasa mencium mereka sepuasnya. Tentunya ini melanggar sunnatullah yang sudah semestinya ada pada diri mereka. Ah, biarlah mereka tumbuh apa adanya.
Pagi ini, saya mengulangi ritual itu. Kali ini saya mencium cukup lama Ayyasy—si bungsu—karena saya tahu hari ini Allah masih berkehendak menitipkannya padaku genap empat tahun. “Sudah besar pula, kau nak rupanya,” batinku.
Maafkan Abi jika sempat-sempatnya Abi ini memelototimu saat kau masih saja bergurau di tengah-tengah sholat berjamaah di masjid. Atau saat Abi menolak dengan keras keinginanmu untuk jajan permen selalu. Ah, kiranya sudah terlalu banyak hitungan Abi ini menolak pintamu.
Tapi nak, Abi masih ingat sekitar dua bulan yang lalu, saat di rumah yang ada hanya kita berdua. Kau pergi saja tanpa pamit ke luar rumah tanpa meminta izin kepada Abimu ini yang sedang berkutat dengan asyiknya di depan komputer. Dan menyadari bahwa rumah ini sudah sepi dari riuh rendah suaramu saat bermain sendiri dengan mainanmu itu.
Abimu memanggil tapi tiada bersaut. Di belakang rumah, di kamar, Abi pun sempatkan untuk membuka lemari—teringat dalam sebuah artikel ada seorang anak yang terjebak lama di lemari es, tapi tiada menemukan engkau. Abi mencoba mencari ke rumah tetangga sebelah, lalu menjauh ke tetangga-tetangga jauh lainnya di satu RT bahkan di lain RT dan hasilnya tetap sama, tiada Abi ini menemukan engkau. Ah Abimu ini panik, nak.
Pikiran buruk pun menghampiri. Ah, jangan-jangan engkau diculik nak. Bergegas Abimu ini mencari ke tempat yang lain. Syukurnya Abimu ini bertemu dengan wanita tua peminta sumbangan yang sempat bertemu denganmu, saat engkau memberinya dengan tangan mungilmu itu.
“Bu, ibu melihat anak saya yang ngasih uang kepada ibu tadi tidak?”
“Oh ya, si eneng itu yah…” Ibu itu menganggapmu anak perempuan, Ayyasy.
“Memang setelah ngasih ibu, dia langsung pergi keluar, makanya Ibu tadi tanya, mau kemana neng? Tapi dia diam saja.” jelas si Ibu.
“Kemana arahnya, Bu?” tanya Abimu. Sang Ibu menunjuk ke arah selatan. Ke arah warung yang menjadi favorit Ayyasy untuk membeli jajanan kesukaannya. Tidak jauh dari tempat Abimu ini berdiri.
”Ah, mengapa tidak terpikir oleh Abimu ini nak, hingga melupakan tempat itu,” batin Abimu.
Bergegas menghampiri, di sana, di dekat warung itu, bergerombol anak-anak yang sedang bermain kelereng. Di pinggirnya, terlihat engkau berdiri menatap mereka sambil mengemut permen merah berbentuk telapak kaki itu.
”Ah, Ayyasy, Ayyasy...akhirnya engkau ada di sini.” Saya peluk ia, erat. Saya gandeng tangannya pulang ke rumah. Lega rasanya, di samping tumpukan rasa bersalah padanya karena membiarkan ia pergi sendirian dan tak menemaninya bermain.
”Kalau mau pergi bilang-bilang dulu yah...”pinta saya padanya.
Kini, pagi ini, memori kilas balik pun terpajang. Saat kami—Abi dan umimu ini—hidup dalam keprihatinan. Hingga premi asuransi jiwa ummimu yang niatnya kekal itu terpaksa dibatalkan agar bisa diambil untuk membiayai persalinanmu. Masih terasa dinginnya lantai saat Abimu ini sujud syukur di rumah bidan bersalin mendengar proses persalinan lancar-lancar saja.
Masih terasa indahnya sebagai hadiah kelahiranmu adalah Abimu ini lulus diklat jurusita dan ujian skripsi. Ah…rejekimu adalah rejeki buat Abimu. Lalu tumbuh kembanglah engkau meniti waktu bersama Abi dan Ummimu. Menangis, berceloteh, berteriak, merangkak, tertatih-tatih berjalan, jatuh dari ranjang goyangmu, berbicara terbata-bata hingga lancar walaupun sekarang huruf r-mu masih tidak jelas seperti Abimu, bertengkar dengan kakakmu, dan saat ini engkau masih saja lucu dengan baju seragam TK-mu yang kebesaran itu. Ya, masih saja lucu…
Selamat ya Nak…Abimu masih saja berusaha bersyukur kepada-Nya karena IA senantiasa mempercayai Abimu untuk menjagamu, memilikimu. Selamat nak, semoga ini akan terbaca olehmu kelak dewasa. Semoga pula kita dikumpulkan di jannah-Nya, bersama kakakmu, Abimu, dan Ummimu tentunya.
Kabulkanlah ya Allah....
Ps. Belum sempat Abimu ini membuat syair seperti dulu.
riza almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
02:24 19 September 2006









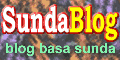


No comments:
Post a Comment