DEMOKRASI BERMUKA DUA vis a vis SYURA
Thursday, September 8, 2005 - DEMOKRASI BERMUKA DUA vis a vis SYURA
Dunia kini telah melihat secara nyata betapa harga dari sebuah demokrasi di bayar mahal dengan kehancuran peradaban dan hilangnya ribuan nyawa akibat perang yang dipaksakan Amerika Serikat (AS) kepada Irak sebagai suatu bangsa dan pemerintahan yang sah.
Dunia pun menjadi mafhum bahwa AS yang mengklaim diri sebagai bangsa dan negeri kampiun demokrasi dan HAM ternyata memaknai sebuah demokrasi sebagai kedok belaka dari wajah buruk berupa kepentingan nasionalnya. Ralph L Boyce—mantan duta besar AS untuk Indonesia —pun mengakui perang ini semata-mata berdasarkan national interest Amerika (Sabili X/2003). Hatta mengingkari makna demokrasi itu dengan tetap mengabaikan PBB sebagai pemegang otoritas dan suara terbanyak masyarakat dunia sampai tetap memaksakan bentuk ekstrim dari ademokrasi berupa kekerasan (perang) sebagai jalan keluar. Padahal Henry B Mayo dan Robert A Dahl selalu menyatakan bahwa nilai demokrasi yang asasi dan asali adalah meminimalisir penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan segala sesuatu (Moch Eksan, 2003).
Dengan demokrasi yang dilandaskan pada kepentingan nasionalnya dan dipaksakan kepada Irak sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berdaulat, maka AS—yang menurut Collin Powell juga disebut sebagai old-democration—pun memunculkan suatu ambigu, yakni AS tetap menginginkan proses demokrasi diterapkan dengan baik di Irak tetapi di lain sisi AS membiarkan sistem monarki dan otokrasi berjalan dengan semestinya di sebagian negara di Timur Tengah, serta membiarkan kekejaman yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
Ambigu demokrasi AS berdasarkan catatan sejarah diterapkan dengan memakai standar ganda, semisal FIS sebagai representasi partai Muslim di Aljazair yang memenangkan pemilu dibatalkan begitu saja kemenangannya oleh rezim militer di sana, dilarang, serta dibubarkan sebagai sebuah partai. Amerika diam saja tidak berbuat apapun karena ada dua hal yakni tak ada kepentingan di sana dan pemenang pemilu tersebut berlabel Islam.
Tidak ada yang aneh di sini karena R James Woosley—mantan Direktur CIA di era Clinton dan sebagai salah satu pengaju proposal penyerangan AS ke Irak—menegaskan demikian, bahwa kalau ada di AS sendiri partai Islam dan memenangkan pemilu hari ini, maka esoknya pemilu harus diulang kembali (Republika, 8 April 2003).
Hal paling sarkas dan berusaha untuk dipahami sebagai suatu kewajaran tampak di sebuah lembaga besar bernama PBB, dengan adanya hak veto yang dipakai oleh lima negara pemenang PD II (AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina) di Dewan Keamanan. Suara mayoritas tidak akan keluar menjadi suatu keputusan bulat dan politis kalau ada hak veto yang dikeluarkan oleh satu saja negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Dalam hal ini AS sering memveto resolusi yang merugikan Israel sebagai sekutu terdekatnya.
Dengan penerapan demokrasi yang ambigu tersebut maka Paul Trenon menyatakan bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem yang ideal untuk mengusahakan kesejahteraan. Di dalamnya penuh kebohongan yang menyeret negara-negara yang tidak punya akar tradisi demokrasi pada kesenjangan hidup.
Maka wajar pula timbul pemikiran dari sebagian Muslim yang menolak sistem demokrasi ini dengan argumen bahwa demokrasi adalah mabda’ (prinsip) impor dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, karena ia ditegakkan pada keputusan suara terbanyak dan dianggap sebagai kebenaran di dalam menegakkan pemerintahan, memperlakukan urusan, dan menguatkan salah satu perkara yang diperselisihkan. Jadi jumlah suara dalam demokrasi menjadi hukum dan rujukan. Maka apa pun pendapat atau gagasan yang mendapatkan dukungan suara terbanyak secara mutlak maupun secara terikat pada suatu waktu, pendapat atau pemikiran itulah yang harus dilaksanakan, meskipun salah atau batil.
Sebelumnya perlu ditegaskan di sini bahwa Islam adalah agama yang syumul sehingga tidak ada suatu sistem hidup yang tidak di atur dalam Islam. Dalam hal penyelesaian masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan maka Islam menjadikan Syura sebagai suatu prinsip utama. Al-Qur’an menguraikannya dalam Al-Baqoroh:233, Asy-Syu’ara:38, dan Ali ‘Imron: 159. Syura atau permusyawaratan adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. (Ensiklopedi Islam 5: 19).
Al-Qurthubi, seorang mufasir yang menukil dari Ibnu Atiyah, menulis: “Musyawarah adalah salah satu kaidah syarak dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barangsiapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengn ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia dipecat”. (Ensiklopedi Islam 5: 19).
Namun mengenai bentuk pelaksanaan Syura, tidak ada nas yang menjelaskannya. Nabi SAW yang telah melembagakan dan membudayakan syura karena ia gemar bermusyawarah dengan para sahabatnya, tidak mempunyai pola dan bentuk tertentu. Karena itu bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan zaman umat Islam.
Namun di sini perlu ditegaskan bahwa objek dari syura’ adalah selain dari ketetapan-ketetapan syari’at yang sudah kongkrit dan dasar-dasar agama serta hal-hal yang sudah diketahui secara pasti. Sehingga dengan ini syura pun memerlukan suara terbanyak dalam memutuskan masalah-masalah ijtihadiyah yang memungkinkan timbulnya banyak pendapat dan pemikiran, dan memang manusia dikondisikan berbeda-beda pandangan dalam hal ini.
Sesungguhnya logika dan syara’, dan fakta mengisyaratkan bahwa harus ada sesuatu yang dipandang kuat. Sedangkan yang dipandang kuat pada waktu terjadi perbedaan pendapat ialah yang mendapatkan suara dan dukungan terbanyak, karena hasil pemikiran dua orang itu lebih dekat kepada kebenaran daripada hasil pemikiran seorang, dan dalam suatu hadits dikatakan: “ Sesungguhnya setan itu bersama yang seorang, sedangkan terhadap dua orang dia lebih jauh “(HR Turmudzi dalam al-Fitan, Hadits Hasan Sahih Gharib).
Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikuatkan adalah yang benar—meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya—dan yang salah harus ditolak meskipun mendapat dukungan 99% suara maka pendapat ini hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah dinashkan secara syara’ secara sah dan sharih yang tidak dapat dipertentangkan serta diperselisihkan lagi meski yang demikian sedikit jumlahnya. Maka menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk hal ini diterapkanlah pernyataan:
“Jama’ah itu ialah yang sesuai dengn kebenaran, meskipun Anda hanya seorang diri.
Adapun masalah-masalah Ijtihadiyah yang tidak ada nashnya, atau ada nashnya tetapi mengandung banyak kemungkinan penafsiran, atau terdapat nash lain yang menentangnya—yang kekuatannya sama dengan nash itu atau lebih kuat, sedangkan untuk menguatkan salah satu tidak ada—maka pengambilan suara merupakan jalan pemecahan yang sudah dikenal manusia dan diterima oleh para cendekiawan yang di antaranya adalah kaum muslim. Juga tidak terdapat larangan syara’ bahkan terdapat nash-nash dan yurisprudensi yang mendukungnya (Yusuf Al-Qaradhawi, 1995:937).
Maka dalam lapangan syura, hal yang sudah qath’I dan pasti menjadi suatu hal yang mutlak tidak bisa dimusyawarahkan, sehingga tidak ada pemungutan suara sekalipun di sini. Sehingga syura tanpa pemungutan suara atau dengannya dalam masalah ijtihadiyah itu Insya Alloh tidak ada kebathilan yang keluarnya. (Untuk lebih jelasnya baca buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradhawy: Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2 hal 915-941, dan Fiqih Daulah dalam Perspektif Alqur’an dan Sunnah hal 181-205).
Sehingga kaitannya dengan demokrasi pada saat ini, pada dasarnya Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah ini dengan suatu sistem yang bernama Syura. Di mana sistem tersebut meletakkan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai patokan utama dan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga demokrasi dalam Islam adalah demokrasi yang berlandaskan 2 wasi’at tersebut. Sebagaimana diuraikan Ustadz Abbas al-Aqqad dalam kitab yang berjudul ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah (demokrasi Islam).
Sehingga bagi mereka yang mengecam Islam tidak mempunyai akar demokrasi, sesungguhnya semuanya telah di atur secara lengkap dan sempurna dalam Islam dengan Syura. Dan sesungguhnya siapa saja dari jama’ah Islam yang menganggap bahwa demokrasi merupakan bagian dari kekufuran atau kemungkaran maka sesungguhnya bisa saja kita katakan bahwa Syura Islam serupa dengan ruh demokrasi atau substansi demokrasi serupa dengan ruh Syura Islam.
Yusuf al_Qaradhawi pun mengatakan Substansi demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka (Yusuf Al-Qaradhawi, 1997: 184). Inilah substansi yang hakiki dari demokrasi, seperti pemilihan umum, meminta pendapat rakyat, menegaskan ketetapan mayoritas, multipartai politik, hak minoritas yang bertentangan kebebasan pers, dan mengeluarkan pendapat, otoritas pengadilan dan lainnya. Apakah demokrasi dengan substansi yang disebutkan di atas tadi bertentangan dengan Islam?
Tentu saja mereka tidak mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci. Dan kita akan melihat bahwa justru ini berasal dari Islam, Islam menolak seseorang menjadi Imam shalat yang tidak disukai orang-orang yang makmum di belakangnya. Di dalam hadits disebutkan, “Tiga golongan yang shalatnya tidak bisa naik di atas kepala mereka sekalipun hanya sejengkal…” lalu beliau menyebutkan yang pertama di antaranya, “Seseorang yang mengimami suatu kaum dan mereka tidak suka kepadanya. (diriwayatkan Ibnu Majah).
Jika dalam shalat saja urusannya seperti ini, lalu bagaimana dengan berbagai urusan kehidupan yang lain dan politik? Tentu Islam telah mengaturnya sedemikian rupa.
Dan perlu ditegaskan di sini bahwa demokrasi yang diterapkan oleh AS itulah yang perlu dilawan, karena sesungguhnya demokrasi bermuka dua bukanlah demokrasi sesungguhnya. Dan bagi mereka yang menuhankan demokrasi sebagai satu-satunya jalan pemecah krisis kemanusiaan lebih spesifik lagi krisis multidimensional di Indonesia, ingatlah sesungguhnya demokrasi tanpa syura hanya akan menjerumuskan kita lebih dalam lagi ke jurang krisis itu.
Saya kembali ingat tanggapan Rizal Malarangeng di medio Nopember pada salah satu talk show tentang sekelompok orang yang menurutnya menggunakan dalih agama untuk melakukan aksi ‘terorisme’ di Bali, tambahnya lagi: tidak ada tempat dan kesempatan bagi Abu Bakar Ba’asyir, Amrozi dkk di alam demokrasi ini, dan demokrasi harus melawan orang-orang seperti mereka. Kini beranikah ia untuk mengatakan bahwa demokrasi pun harus bersama-sama melawan AS dan tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada AS untuk menggunakan jalan kekerasan? Tidak, berarti ia pun bermuka dua, karena ia tidak berani sedikitpun untuk menyetujui langkah-langkah pemboikotan produk AS bahkan sampai berani mengatakan bahwa langkah tersebut emosional dan sia-sia, sekarang mana langkah perlawanannya…? Tidak ada karena ia bukan siapa-siapa, karena ia hanya seorang ‘doktor’ lulusan AS, ia hanya peneliti di CSIS, dan ia hanya seorang Islam Liberal.
Sekarang saatnya bagi kita umat Islam untuk melawan demokrasi AS dengan syuro. Sekecil apapun perlawanan itu Insya Alloh akan bernilai. Itu saja. Yang benar datangnya dari Alloh semata, dan yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Allohu’alam.
riza almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
di antara kumpulan arsip lama 2003
15:31 08 September 2005
Maraji’:
1. Al-qur’anul Kariim;
2. Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, Yusuf Al-Qaradhawy, Pustaka Al-Kautsar, 1997
3. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Yusuf Al-Qaradhawy, Gema Insani Press, 1995;
4. Ensiklopedi Islam 5, PT Icktiar Baru van Hoeve, 1997;
5. Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi, Gema Insani Press, 1998;
6. Ensiklopedi Keluarga A-Z, PT Cipta Mitra Sanadi, 1991;
7. Sabili 19/X/2003;
8. Sabili 20/X/2003;
9. Republika 8 April 2003;
10. Kompas 1 April 2003.









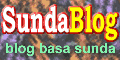


2 comments:
syuro adalah hukum ALLAh subhanahu wa ta'ala, sedangkan demokrasi adalah hukum thoghut. Maka batillah orang yang mengatakan demokrasi islam=syuro. Dalam demokrasi suara ulama sama dengan suara pelacur, ALLAHU AKBAR. sungguh sebuah kesesatan yang nyata.
Jangan terlalu berlebihan menilai. :-)
Post a Comment