Behind the Scene: Bojo Loro
Friday, January 6, 2006 - Behind the Scene: Bojo Loro
Email itu bertubi-tubi masuk ke inbox saya. Telepon genggam Qaulan Sadiida pun tiada berhenti deringnya menerima short message services. Jikalau saya punya alat komunikasi sepertinya (hare gene, masih juga nggak punya?) , mungkin saya akan mengalami hal yang sama dengan Qaulan Sadiida.
Beragam komentar pun datang untuk membuat ending yang lebih bernas bahkan mengusulkan untuk membuat sequel—yang saya pikir nantinya akan tersia-sia seperti judul sinetron Tersanjung dengan tujuh episodenya.
Pula dengan membawa misi terselubung anti poligami dan dendam gendernya dengan menjerumuskan ke lembah kesengsaraan yang paling dasar untuk si Bima. Hingga ada yang sengaja datang ke meja kerja saya hanya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik Bojo Loro.
Saya cuma bisa menjawab kepada mereka, ”That is a fiction, Bro...” Tidak lebih. Jawaban itu tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang telah memberikan komentar tentang pilihan pada happy, bad, or thrust ending , serta pada setiap bulir bening yang jatuh saat membacanya—satu email dan satu silaturahim langsung menyatakan itu.
Brother, jangan malu untuk menangis, jika menangis itu membuat jiwa kita lebih tercerahkan menyadari kekhilafan diri. Bahkan saya tak bisa membendung bulir-bulir bening ini jatuh saat membaca buku ”Bukan di Negeri Dongeng: Kisah Nyata para Pejuang Keadilan”, salah satu ceritanya ditulis oleh seorang wanita—Mbak HTR—yang sering engkau katakan: ”cewek ini berkali-kali membuatku menangis”.
Pula saat saya membaca buku ”Memoar Cinta di Medan Dakwah: Catatan Harian Seorang Aktivis” yang ditulis oleh ustadz Cahyadi Takariawan—seringkali dianggap sebagai Ketua MPR karena mirip dengan ustadz Hidayat Nurwahid apalagi beliau sering pakai baju batik.
Tentunya ini semua tak bisa dilepaskan oleh pasangan tandem saya, Qaulan Sadiida, yang dengan segenap hatinya pula berusaha untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi bagiannya. Terus terang saja, cita rasa bahasanya tak bisa terlampaui oleh saya. Maka hasil akhirnya pun membuat saya tak lelah untuk berulangkali membaca draft Bojo Loro. Pesan singkat darinya cuma satu saat telah menyelesaikan itu: ”Semuanya dari sini,” sambil tangannya menunjuk ke arah dadanya. Hati. Segala puji hanya untuk Allah.
Maka siapa yang tak akan tergetar mendengar senandung ayat-ayat Allah yang dikeluarkan dari hati-hati guru, ustadz, dan orang-orang yang ikhlas. Maka siapa yang dapat menghalangi keindahan dari cerita yang dibuat dengan tangisan usai salat malam oleh Mbak kita yang satu ini dengan cerpen: ”Ketika Mas Gagah Pergi”.
Maka siapa pula yang menyangkal keromantisan padang pasir saat Habiburrahman menulis ”Ayat-ayat Cinta”-nya dengan menangis juga. Maka siapa yang mengingkari keikutdukaan kita saat membaca tulisan Abu Aufa di kala ia ditinggalkan anak perempuannya yang berumur sehari bernama: Hikari.
Sebagaimana seorang teman menggambarkan kesedihan itu layaknya kesedihan Muhammad Sang Musthofa ditinggalkan Ibrahim tercinta. Layaknya kesedihan bangsa ini saat dipertontonkan tsunami 12 purnama yang lalu atau banjir bandang baru-baru saja.
Hingga dari mula itu, seorang guru menulis saya sampai berkata: ”itulah kedahsyatan hati, itulah kedahsyatan fiksi, hingga orang sampai tidak bisa membedakan realitas kehidupan kita itu fakta atau fiktif.”
”Brother, that is a fiction,” ulang saya. Dengan sedikit imajinasi liar tentunya—saya tak bisa membayangkan pula keliaran imajinasi yang dimiliki JK Rowling dengan Harry Porternya, JRR Tolkien dengan The Lord of The Ring-nya, atau Afifah Afra Amatullah dengan Genderuwo Terpasung-nya.
“Brother, That is a fiction…” ulang saya. Tapi tak menyangkal pula bahwa fenomena itu memang benar-benar terjadi pada sebagian dari kita hanya karena diawali dengan chating, sms, dan email iseng sehingga pada akhirnya melonggarkan ikatan dan batasan yang dulu dipegang erat saat di kampus.
“Brother, that is a fiction…” ulang saya sembari menyerahkan selembar tissue wangi kepada teman yang meneteskan air mata. Bukan karena meratapi nasib Kinanti, bukan karena Bojo Loro, tapi karena di atas mejanya ada semangkuk irisan bawang merah. (Maaf paragraf ini benar-benar fiksi karena melihat Squidward yang menangis bukan karena melihat adegan Spongebob meratap tak rela melepaskan kuda laut liarnya, tapi karena ada semangkuk bawang bombay di dekatnya;-)
”Brother, that is a fiction....” ulang saya. Arahkan telunjukmu ke hati, rasakan dan dengarkan denyutnya. Hingga kau rasakan rasa setara memiliki bojo loro.
riza almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
00.15 06 Januari 2006









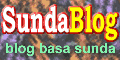


No comments:
Post a Comment