aku merinduimu
Monday, September 12, 2005 - aku merinduimu
Hujan masih saja merintih menghitung genting di luar sana. Tak peduli pada malam yang kian tenggelam dalam selimut halimun. Tak peduli pada diriku yang memandang kegelapan di balik jendela kamar. Tak peduli padaku yang melanglangkan ingatan-ingatan pada masa-masa lalu.
Tak peduli padaku yang tiba-tiba teringat Zatoichi tercenung saat hujan tiba di rumah Bibi Oume. Memandang dan merenungi hujan itu, mengingat pertempuran melawan delapan orang yang dengan mudahnya semuanya ia tebas. Membuat tanah becek semakin becek dengan darah.
Tidak, tidak, saat ini, saat hujan ini, aku lebih merindui Tasikmalaya. Merindui sudut-sudut salah satu desanya. Merindui dinginnya malam. Merindui subuh yang semakin menggigit. Merindui cahaya matahari pagi. Merindui kicau burung. Merindui gemericik air pancuran. Merindui kokohnya saung di lebak. Merindui dua rakaat dhuhanya. Merindui dzikirnya. Merindui perjalanan pulang di pematang sawah. Merindui ikan-ikan di kolam belakang. Merindui kepulan uap nasi. Merindui sambal terasinya. Merindui duh…Gusti, saat ini aku merindui Tasikmalaya. Merindui sudut-sudut salah satu desanya.
Salah satu desa itu adalah Margalaksana di wilayah Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Desa yang menjadi tempat pelarian paman-pamanku waktu tahun 60-an, sewaktu gerakan PKI mendapat tempat di republic ini. Sebagai ketua gerakan dan aktivis kepemudaan Nahdhotul ‘Ulama Ketanggungan, Brebes , beliau bersama adik-adiknya menjadi sasaran empuk untuk diintimidasi bahkan bila perlu dibantai. Maka untuk sementara, menunggu arah angin berubah, mereka hijrah ke sana. Namun hijrah itu tidak sementara, keempat paman itu memperistri gadis, beranak pinak, dan bermata pencaharian di sana hingga kini.
Jadilah di sana tempat aku menghabiskan masa liburan sekolah yang panjang. Dan terakhir adalah sepuluh tahun yang lampau. Saat aku masih menjadi mahasiswa Program Diploma Keuangan Spesialisasi Perpajakan. Liburan panjang itu tiba. Kini saatnya aku pulang kampung—setelah berjuang habis-habisan dengan ujian-ujian sulit—seperti kebiasaan teman-teman kampus yang pada pertengahan tahun berritual untuk mengosongkan kampus, kecuali para mahasiswa yang menjadi panita penyambutan mahasiswa baru.
Tiba-tiba terbersit dalam pikiranku, kiranya aku sempatkan beberapa hari terlebih dahulu di Tasikmalaya baru setelah itu pulang ke Jatibarang, Indramayu. Maka bersiap-siaplah aku berpetualang.
Dari kampus ba’da sholat Jum’at, aku pun melaju dengan angkutan umum menuju stasiun Senen untuk mengejar Kereta Ekonomi Galuh jurusan Tasikmalaya – Banjar. Ini pengalaman pertama bagiku ke Tasimalaya dengan menggunakan jasa kereta api.
Kereta ekonomi yang seharusnya berangkat jam tiga sore, molor satu jam lebih dari jadwal semula. Kereta berangkat meninggalkan stasiun dengan tidak banyak penumpang yang memenuhi gerbong. Sehingga aku dapat meluruskan kaki ke kursi depanku yang kosong. Sambil membaca buku yang aku bawa, sesekali aku melihat ke luar jendela, melihat senja yang mulai turun dan meninggalkan jejak-jejak jingganya.
Adzan maghrib mulai berkumandang saat memasuki daerah Purwakarta yang berkelok-kelok. Aku sangat menikmati sayup-sayupnya yang keluar dari bukit-bukit nun jauh di sana. Oh Rabb, aku merindui sayup ini.
Tiba-tiba ketika aku sedang berasyik masyuk, ada seruan kepada seluruh penumpang untuk diharapkan menuju ke gerbong depan karena gerbong yang saya naiki dan masih ada lima gerbong lainnya di belakang tidak berpenerangan. Sehingga dikhawatirkan terjadi kerawanan, oleh karena itu kondektur kereta menyarankan demikian. Aku pun menurutinya dan mencari tempat duduk yang masih ada di gerbong yang terang benderang itu.
Bandung pun terlewati begitu saja, tanpa aku sadari karena terlelap oleh kantuk yang menyerangku. Namun ada yang eksotik dengan stasiun di antara bandung dan Tasikmalaya, yang kereta ini sempat untuk berhenti lama di sana, sayangnya aku lupa stasiun itu.
Dengan bangunan peninggalan zaman Belanda, kubah tinggi di atas selasarnya, dan hanya diterangi lampu bohlam yang temaram benar-benar membuatku terasa bukan berada di zaman moderen, namun seperti berada di masa-masa kemerdekaan. Tinggal aku menuliskan merdeka atau mati! di tembok stasiun maka lengkap sudah flashback ini. Benar-benar aku tertegun cukup lama. Rasa melankolisku kembali bangkit mengenang masa-masa perjuangan dulu. Duh Gusti aku merinduinya.
Tasikmalaya sudah di depan mata. Perjalanan memakan waktu kurang lebih tujuh jam. Jarum pendek jam di statiun sudah mengarah ke angka sebelas. Aku mencari mushola untuk menunaikan sholat jamakku, namun pintu mushola sudah terkunci rapat dan gelap. Akhirnya aku putuskan untuk sholat di luar stasiun.
Pada saat keluar dari stasiun itu aku baru tersadar bahwa ternyata angkutan kota sudah tidak beroperasi lagi pada jam-jam seperti ini. Maka dengan berbekal petunjuk dari orang-orang sekitar stasiun aku melangkahkan kaki ke Masjid Raya Tasikmalaya. Sengaja aku tidak naik ojek supaya bisa irit maklum aku masih mahasiswa.
Perjalanan menuju masjid raya terasa jauh, namun aku bertekad untuk ke sana dengan harapan aku bisa istirahat dan tidur di sana, dan dengan semakin semakin mendekati pusat kota aku kiranya mendapatkan angkutan yang mungkin saja masih beroperasi.
Masjid Raya setali tiga uang dengan mushola yang ada di stasiun. Terkunci rapat, tidak ada satu dari banyak pintu yang sudi membuka sedikit untuk aku. Aku pun sholat di teras masjid. Niat aku untuk beristirahat dan tidur hingga pagi terpaksa aku batalkan, karena aku tidak kuat menahan dingin angin malam di teras berlantai marmer itu. Oh ya, waktu itu aku tidak punya jaket lho.
Angkutan kota benar-benar nihil. Setelah bertanya kesana kemari, aku mendapatkan keterangan bahwa angkot baru ada pukul lima pagi. Wah, tidur dimana aku. Dan terminal pun masih sangat jauh dari masjid. Akhirnya ada seorang tukang ojek yang masih berbelas kasihan denganku. Ia bersedia mengantarkanku ke terminal hanya dengan setengah ongkos perjalanan.
Kepada tukang ojek itu aku menghaturkan banyak terimakasih saat aku telah sampai di Terminal. Di sana aku hanya menjumpai mobil angkutan yang cuma beberapa. Lagi-lagi aku mengalami keterkejutan angkutan pedesaan yang menuju Salawu baru akan datang dan berangkat jam dua nanti. Terpaksa aku mencari kenyamanan di sebelah Tukang Ulen Bakar. Aku hanya bisa memandangi saja, tak bisa menikmati makanan yang termasuk favoritku itu. Maka aku terduduk meringkuk, merapatkan tangan ke lututku, menahan dingin dan lapar selama satu jam lebih.
Penderitaanku berakhir saat angkutan pedesaan itu tiba dan langsung terisi penuh oleh banyak penumpang. Kulepaskan lelah dan penatku dengan tidur selama kurang lebih satu jam perjalanan menuju Margalaksana.
Akhirnya sampai juga di rumah “uwak”ku yang persis di pinggir jalan besar Garut Tasikmalaya. Aku menghirup udara sepertiga malam terakhir dalam-dalam dan kehembuskan sekuat-kuatnya. Lega rasanya.
Tapi dikejauhan tiga orang sepertinya bergegas menuju ke arahku. Aku tidak pedulikan mereka, aku pikir mereka adalah para peronda kampung. Segera saja aku masuk ke halaman rumah, dan mengetuk pintu. Lima menit lamanya aku mengetuk sampai beberapa saat kemudian pintu itu pun terbuka. Di seberang jalan, kulihat tiga orang itu masih memandangi aku.
******
Sarapan yang menggugah selera bersama keluarga uwak. Nikmat sekali, ceria, ramai dengan gurauan. Dari situlah aku mendengar bahwa aku sempat dicurigai sebagai salah satu anggota komplotan maling oleh para peronda kampung. Tapi semuanya bisa dijelaskan oleh uwakku waktu ia sholat shubuh di masjid. Aku tersenyum saja. Ah teganya mereka menuduh aku yang sedang kelaparan pula.
******
Sungguh kawan, aku masih tentang perjalanan itu. Masih aku merindui semuanya itu. Merindui dhuha di lebak itu. Hingga terinspirasi semua itu, aku buat puisi ini:
matahari dhuha merambati waktu
ketika sinarnya menghangatkan
pucuk-pucuk dedaunan
menggiring hati ke kehampaan
yang meradangkan diri
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari
sungai bening mencumbui tanah
ketika riaknya membasahi
akar-akar pepohonan
melautkan hati ke kehilangan
yang membakarkan diri
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari
burung kecil menghiasi langit
ketika kicaunya meramaikan
putih-putih awan
menerbangkan hati ke ketinggian
yang menyesakkan diri
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari
rokaat pendek mengukir sajadah
ketika dzikirnya membisikkan
rongga-rongga dada
mengkhusukkan hati ke kesucian
yang membersihkan diri
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari
matahari ashar mengguliri sore
ketika lelahnya menguliti
pori-pori tubuh
mencabikkan hati ke kemeranaan
yang menyakiti diri
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari
aku lelah
menunggu berlalunya kala yang amat pelan berlari itu
karena senin masih jauh
di ufuk...
****
Aku menikmati liburan itu di sana. Menyusuri pematang sawah, jalan-jalan lengang, memancing ikan, ngaliwet di gunung, berselimut tebal saat malam, hingga rokaat-rokaat di sepertiga malam terakhir. Duh, indah nian rasanya. Duh, gelegaknya rindu ini. Duh....
Kawan, kapan aku bisa kembali ke sana, atau memutar kembali waktu yang telah berjalan?
Kini aku sedang merindui Tasikmalaya dan sudut-sudut desanya.
****
riza almanfaluthi
dedaunan di ranting cemara
di antara rindu untukmu
04:30 12 September 2005









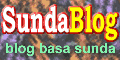


No comments:
Post a Comment